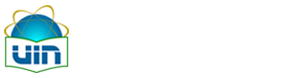Saatnya Profesor Berhenti Berlari
Perpustakaan UIN Jakarta, Artikel Sivitas — Hari ini (Rabu, 14/01), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta kembali mengukuhkan tujuh orang dosen sebagai Guru Besar atau Profesor. Momen ini layak dirayakan sebagai puncak perjalanan akademik yang panjang setelah bertahun-tahun belajar, meneliti, mengajar, dan mengabdi. Namun, pengukuhan sejatinya bukan garis finish. Ia adalah pintu masuk ke babak baru, ketika seorang akademisi justru memiliki kemewahan yang paling langka di kampus hari ini: "kesempatan untuk berhenti berlari".
 Selama bertahun-tahun, banyak dosen dipaksa berlari. Berlari mengejar publikasi, berlari memenuhi indikator kinerja, berlari mengisi borang dan laporan, serta berlari agar tidak tertinggal dalam sistem yang mengagungkan kecepatan. Dalam situasi seperti itu, kepakaran sering kali tumbuh secara fungsional yang berusaha untuk memenuhi syarat administratif, tetapi tidak selalu sempat matang secara intelektual. Gelar profesor pun, dalam sebagian kasus, lebih mencerminkan keberhasilan menavigasi sistem ketimbang kedalaman keilmuan.
Selama bertahun-tahun, banyak dosen dipaksa berlari. Berlari mengejar publikasi, berlari memenuhi indikator kinerja, berlari mengisi borang dan laporan, serta berlari agar tidak tertinggal dalam sistem yang mengagungkan kecepatan. Dalam situasi seperti itu, kepakaran sering kali tumbuh secara fungsional yang berusaha untuk memenuhi syarat administratif, tetapi tidak selalu sempat matang secara intelektual. Gelar profesor pun, dalam sebagian kasus, lebih mencerminkan keberhasilan menavigasi sistem ketimbang kedalaman keilmuan.
Buku The Slow Professor: Challenging the Culture of Speed in the Academy karya Maggie Berg dan Barbara K. Seeber memberi peringatan penting pada fase ini. Budaya percepatan, menurut penulis buku, telah mengubah universitas menjadi ruang kerja yang sibuk tetapi kelelahan secara intelektual. Kecepatan dijadikan ukuran mutu, sementara waktu untuk berpikir, membaca mendalam, dan menulis secara reflektif semakin terpinggirkan.
Dan di sinilah justru makna pengukuhan sebagai professor dimulai, seorang akademisi seharusnya mulai mengambil jarak dari logika tersebut. Profesor tidak lagi berada pada fase membuktikan kelayakan administratif, melainkan pada posisi moral dan intelektual untuk menentukan arah keilmuan. Di titik inilah, berhenti berlari menjadi tindakan yang bermakna, bukan sebagai bentuk penolakan tanggung jawab, melainkan sebagai upaya merebut kembali esensi akademia.
Babak baru ini semestinya diisi dengan karya-karya orisinal yang lahir dari kedalaman, bukan keterpaksaan. Buku yang ditulis bukan karena tuntutan angka, riset yang dikerjakan bukan demi laporan, dan pengajaran yang dilakukan bukan sekadar memenuhi beban kerja. Profesor, pada tahap ini, diharapkan menjadi penentu agenda keilmuan, bukan sekadar pengikut ritme sistem.
Dalam konteks Indonesia, ajakan ini menjadi semakin relevan. Perguruan tinggi tengah giat memperbanyak profesor, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa gelar tersebut berbanding lurus dengan kontribusi intelektual yang bermakna bagi masyarakat. Profesor bukan hanya simbol prestise institusi, melainkan rujukan keilmuan dan suara kritis publik. Tanpa keberanian untuk melambat, profesor berisiko terjebak dalam rutinitas administratif yang justru menggerus otoritas intelektualnya sendiri. Tentu, tidak semua profesor memiliki ruang yang sama untuk melambat. Beban struktural dan tuntutan institusional tetap nyata. Namun, posisi profesor memberi legitimasi untuk mulai menegosiasikan ulang relasi dengan waktu, produktivitas, dan makna kerja akademik. Jika tidak pada tahap ini, lalu kapan?
Pengukuhan guru besar seharusnya menjadi momen refleksi kolektif. Bahwa puncak karier akademik bukanlah saat untuk berlari lebih kencang, melainkan saat untuk berjalan lebih jernih. Dari sinilah karya-karya besar lahir, bukan dari percepatan tanpa henti, melainkan dari keberanian untuk berhenti, berpikir, dan menulis dengan penuh tanggung jawab intelektual.
Selamat mengalami pelambatan teman-teman Para Guru Besar, kami menanti perjalanan keilmuan yang sesungguhnya.
#Agus_Rifai
Untuk update berita dan informasi lebih lanjut, bisa di akses: